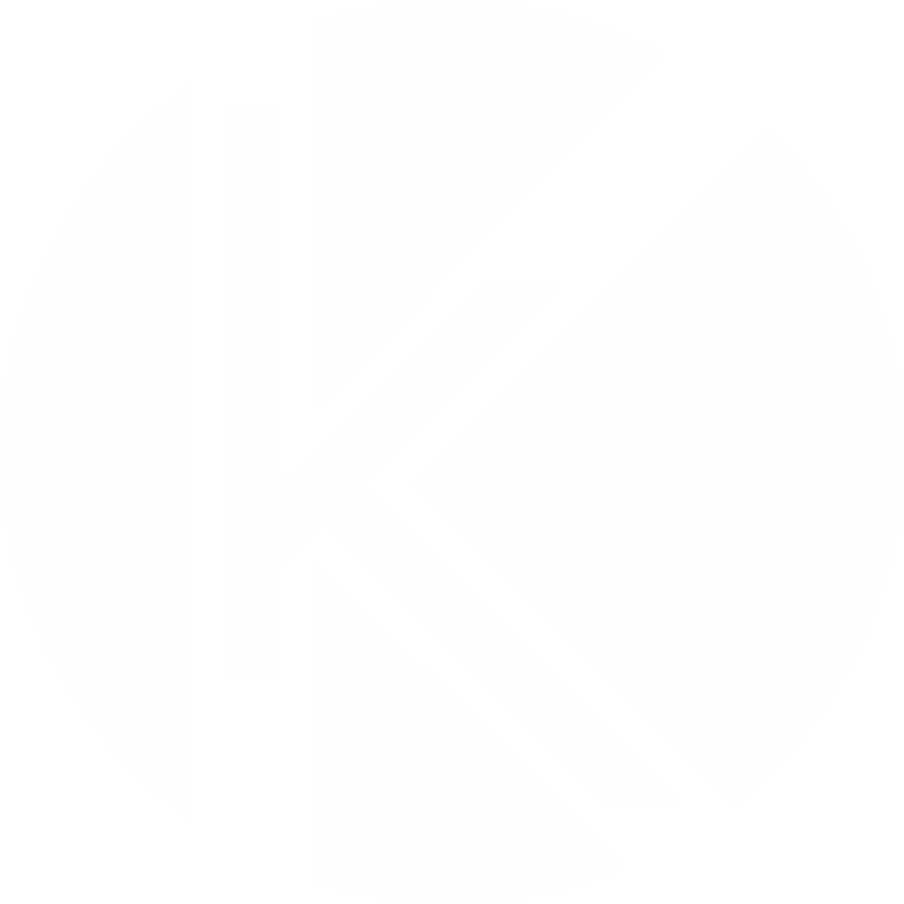Peristiwa
Melihat Awal Pembentukan Kota Samarinda serta Hubungan Kesultanan Kutai dengan Diaspora Bugis

Pemandangan Sungai Mahakam di Samarinda pada 1929 (diilustrasikan dari foto milik Leiden University Libraries/KTLV).
Hari ini, tepat 354 tahun lampau, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Samarinda. Bagaimana sejarah panjang kota menurut penekun literasi?
Ditulis Oleh: Chai Siswandi
Jum'at, 21 Januari 2022
kaltimkece.id Riwayat penduduk dari Sulawesi Selatan yang bermigrasi ke timur Kalimantan sangat panjang. Sejak berabad-abad silam, orang-orang Bugis telah menghuni tanah Kutai tepatnya di Samarinda. Satu dokumen penting menceritakan riwayat tersebut. Dokumen ini disebut Salasila Bugis yang dimuat dalam tulisan SW Tromp. Judulnya Eenige Mededeelingen Omtrent De Boginezen Van Koetei.
Perjanjian orang-orang Bugis juga menjadi bagian dalam Silsilah Raja Dalam Negeri Kutai yang lebih dikenal dengan Salasilah Kutai. Dokumen-dokumen tersebut menjadi penanda zaman. Bahwasanya, sejak lama orang-orang Bugis memiliki kedudukan penting dalam sejarah Kutai, baik dalam jalinan relasi maupun genealogi.
Tromp menyebutkan, orang Bugis pada mulanya menetap di Kutai Lama, kini Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Mereka datang untuk berdagang. Awalnya, satu dua perahu. Jumlah mereka meningkat menjadi empat atau lima perahu dan begitu seterusnya sampai mendirikan kampung. Komunitas ini membuat perjanjian pemerintah yang berkuasa yaitu Kesultanan Kutai Kertanegara. Orang-orang Bugis diberi kekuasaan mengatur pemerintahan dan memilih Pua Ado sebagai pemimpin.
Masih di Kutai Lama, Pua Ado dinikahkan dengan kerabat kerajaan. Akan tetapi, kepala istri Pua Ado dijadikan tijak tanah sultan dalam upacara Erau. Perlakuan itu menimbulkan sakit hati. Pua Ado pergi meninggalkan tanah Kutai untuk bergabung dengan bajak laut Sulu yang menyerang Kutai kemudian.
Selepas peperangan, Kesultanan Kutai memutuskan memindah pusat pemerintahan dari Kutai Lama ke hulu Sungai Mahakam yaitu Pemarangan, Jembayan. Orang-orang Bugis yang telah membentuk kota pelabuhan Samarinda kembali membuat perjanjian dengan Sultan Kutai. Tromp menyebutkan, sultan yang terlibat dalam perjanjian itu kemungkinan Anom Pandji Mendapa ing Martapura.
Menurut Prof Zainal Abidin, adalah adat di Sulawesi bahwa setiap pergantian raja atau pejabat, diadakan perjanjian pemerintahan atau lebih tepat rumus janji harus diulang kedua pihak. “Maka tidaklah mengherankan kalau Puak Ado II dan seterusnya La Mohang Daeng Mangkona mengulangi lagi perjanjian 1668, dan adalah adat di Sulawesi Selatan bagi pendatang baru untuk melaporkan diri pada raja di negeri baru,” demikian Prof Zainal Abidin dalam Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan (1999, hlm 207).
Meringkas tulisan Tromp, permukiman dan sistem pemerintahan di bawah Pua Ado ini sudah ada sejak Sultan Kutai berkedudukan di Kutai Lama. Naskah ini memuat pengakuan bahwa Samarinda adalah kota pelabuhan yang dibangun orang-orang Bugis. Perjanjian di Pemarangan juga bukan perjanjian pertama. Dengan demikian, tidak serta-merta tahun pembaruan perjanjian dalam naskah Tromp ini dianggap sebagai tahun berdirinya permukiman Bugis di tanah Kutai.
_____________________________________________________PARIWARA

Tromp juga menulis tentang relasi pemerintahan Kutai dan orang-orang Bugis yang pasang-surut. Namun, menurut Knappert, orang-orang Bugis kemudian dipercaya sepenuhnya ketika kesultanan menghadapi keadaan sulit yang memerlukan dukungan mereka. “Telah beberapa kali orang Bugis yang turut menegakkan kesultanan (Kutai) telah memberikan layanan yang sangat baik jika terjadi gangguan,” tulis Knappert dalam Behschrijving Van De Onderafdeeling Kotei (hlm 591).
Sejarawan Kaltim, Asli Amin, berpendapat bahwa jasa pertama dari suku Bugis kepada Kerajaan Kutai pada waktu pusat kerajaan di Pemarangan diserang bajak laut Soeloe. Perompak ini dipimpin Datuk Tan Patranalela. Tentara Bugis di Samarinda Seberang, di bawah pimpinan Pua Ado La Made Daeng Punggawa, mengusir mereka dengan bantuan empat andriguru dan tentara Kutai. Pertempuran ini dikenal dengan “Perang Bungka-bungka”. Peperangan berlangsung di tepi sungai Mahakam (pantai) yang berlumpur. Bungka-bungka bermakna lumpur.
“Selanjutnya, ketika Aji Kedok gelar Aji Sultan Muhammad Alijidin memangku jabatan raja (sementara putra mahkota masih di bawah umur) merebut takhta Kerajaan Kutai Kertanegara, kembali orang Bugis memainkan peranan membantu sultan Muhammad Muslihuddin untuk duduk kembali ke atas takhtanya (Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai, 1975, hlm 50).”
Pembentukan Awal Samarinda
Kontrak Kerajaan Banjarmasin dengan VOC mengenai perdagangan lada ditandatangani pada 1635. Komandan Gerret Thomassen Pool pun memasuki Mahakam untuk bernegosiasi. Ia meminta Sultan Kutai Sinum Panji Mendapa ing Martapura melarang pedagang Jawa dan Bugis berdagang di wilayah Kutai. Negosiasi ini bagian dari permintaan Banjarmasin kepada Belanda. Banjarmasin waktu itu menganggap Kutai di bawah kekuasaannya dan ingin memiliki supremasi perdagangan di Mahakam.
Menurut Ita Samtasiyah Ahyat, Kutai tidak mengakui klaim Banjarmasin. Setidaknya, sampai 1739, tidak ditemukan kapal-kapal dari Banjarmasin yang berdagang di Kutai (hlm 54). Ketiadaan kapal dagang Banjarmasin ke Kutai berlangsung setidaknya hingga hampir pertengahan abad ke-18.
Perjumpaan Belanda dengan sultan menjadi keterangan penting mengonfirmasi silsilah Sultan Kutai. Sekaligus memberi keterangan historis bahwa sebelum Samarinda ada, Kutai Lama sudah ramai dikunjungi pedagang Jawa dan Bugis.
Prof Zainal Abidin dalam bukunya Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar menyebutkan, emigrasi besar-besaran orang-orang Bugis Wajo dimulai pada 1667. Waktu itu, benteng Ujung Pandang baru direbut Speelman-Arung Palakka. Lontara’ Sukku’na Wajo’ menyatakan, dalam pertempuran di Somba Opu dan Ujung Pandang itu, kurang lebih 10 ribu orang Wajo mengambil bagian di bawah pimpinan Arung Matoa Wajo La Tenrilai’ To Sengngeng. Sebagian mereka, ditambah orang-orang yang berdiam di Kampung Wajo di Makasar, kemungkinan merantau ke Kalimantan Timur. Menurut de Graaf, orang-orang Wajo atas izin Sultan Kutai membentuk “republik demokratis” di Kalimantan Timur yang mereka namakan Samarinda (hlm 56).
Pendapat de Graaf sesuai dengan catatan Eiisenberger yang menyatakan Samarinda dihuni orang-orang Bugis mulai 1668. Mereka memilih seorang pemimpin yang bergelar Puak Adok (1936, hlm 9). Istilah Puak Adok berasal dari istilah Puang Adek yang dahulu dipakai kepala pemangku adat di Wajo. Sebenarnya pula, telah menjadi pengetahuan umum di Hindia Belanda pada masa lalu bahwa tahun berdirinya Samarinda adalah 1668.
Dalam Ensiklopedia Hindia Belanda (1918), disebutkan, “Pendirian pemukiman Bugis berawal pada 1668, sementara ia dulu eksklusif tinggal di Samarinda, mereka sekarang ditemukan hampir di seluruh negeri, menyebar, dan keberadaan mereka dianggap penting bagi perdagangan. Orang-orang Bugis di Kutai sebagian besar berasal dari Wajo dan hanya sebagian kecil dari Bone dan Soppeng. Menjelang akhir abad ke-17, orang-orang Bugis telah membangun tempat perdagangan yang sekarang bernama Samarinda, yang kemudian segera mereka adopsi atas saran Pemerintah Kerajaan Kutai untuk memilih kepala suku yang bergelar Pua Ado; karena penunjukan itu tidak dilakukan oleh pangeran tetapi dengan pemilihan bebas orang Bugis. Sedangkan kerajaan hanya harus meratifikasi pilihan tersebut. Pilihan dibuat dengan istilah “kepala manang” atau per kepala rakyat.” (hlm 375).
Kasus hukum di permukiman Bugis di Samarinda akan diserahkan penyelesaiannya kepada Pua Ado. Selanjutnya, dalam Ensiklopedia Oleh Hindia Belanda yang dibuat DG Stibbe pada 1939, Samarinda disebut sebagai permukiman Bugis yang berdiri sejak 1668.
Menurut Lontara’Sukka’na Wajo’ (LSW), Andi Zainal Abidin menyatakan, saat Wajo di bawah dominasi Arung Palakka dan VOC dari 1670 sampai 1736, terjadi kelaparan yang hebat. Perdagangan orang-orang Wajo praktis terhenti karena larangan berdagang dengan dunia luar. Keadaan ini mendorong migrasi lebih besar ke berbagai wilayah nusantara termasuk Samarinda.
“Dapatlah diperkirakan bahwa Samarinda pada 1668 belum merupakan kota tetapi kampung. Ia berkembang pesat mungkin setelah Wajo dikalahkan total oleh pasukan La Tenrittatak pada 1 Desember 1670 ketika Tosora, ibu kota Wajo, dapat dihancurkan,” tulis Zainal Abidin (hlm 205).
Setelah itu, Samarinda berkembang menjadi bandar perdagangan. Terlebih, setelah kelak rombongan La Maddukelleng tiba di Kalimantan Timur. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa pada waktu La Pattelok Amanna Gappa hendak menyusun kitab Undang-Undang Hukum Pelayaran dan Perniagaan yang selesai pada 1676. Ia mengadakan konsultasi dengan Matoa-Matoa Paballuk (konsul dagang) di Kampung Wajo di Makasar. Kalau telah ada Matoa Pabbaluk di suatu bandar, berarti tempat itu sudah berkembang menjadi kota. Maka dapat disimpulkan, Samarinda yang mulanya kampung pada 1668 mulai menjadi kota pada akhir 1670 dan permulaan 1671 dan sudah berkembang pada 1676 ketika Amappa Gappa selesai mengodifikasi undang-undangnya (hlm 206).
Ini juga menandakan pada masa itu, keberadaan permukiman Wajo di wilayah timur Kalimantan telah diketahui orang Bugis di Sulawesi. Hal ini menjadi pengetahuan penting bagi diaspora Bugis yang datang kemudian. Mereka berangsur-angsur bertambah seiring waktu bahkan memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin sendiri dan mengatur perdagangan di Samarinda.
Dalton, petualang Inggris yang melakukan perjalanan berkeliling Kutai dalam catatannya yang ditulis pada 1828 menyebut, Samarinda sebagai kampung utama orang-orang Bugis di Kutai. Menurut Dalton, alasan utama orang-orang Bugis seperti memiliki kekuasaan lebih dibanding penduduk asli di Samarinda karena mereka menguasai perdagangan garam.
Sementara oleh Pelras, dikatakan orang Bugis Samarinda juga memonopoli impor beras, garam, rempah-rempah, kopi, tembakau, opium, porselen, kain, besi, senjata api, sendawa (bahan mesiu), dan budak.
“Mereka juga diberi hak membentuk pemerintahan serta mengorganisasi diri sendiri di bawah pimpinan seorang kepala bergelar Pua Ado—putri sulung pemangku pertama gelar tersebut dinikahkan dengan putra La Ma’dukelleng lainnya—dan dewan yang terdiri beberapa orang nakhoda. Sejumlah pemimpin Bugis diberi gelar kehormatan oleh Sultan (Kutai) sehingga kedudukan mereka sejajar dengan bangsawan Melayu dan keturunan mereka dapat dikawinkan dengan keturunan penguasa kerajaan (Manusia Bugis, 2005, hlm 372-373).”
Saat La Maddukelleng tiba di Kalimantan, ia membina hubungan politik dengan penguasa setempat lewat perkawinan dengan menikahi putri Sultan Pasir. Anak perempuan pasangan tersebut kemudian dinikahkan dengan Sultan Idris dari Kutai saat La Maddukelleng menjadi Sultan Pasir.
Mengenai Nama Samarinda
Dalam buku Republik Indonesia, Kalimantan yang diterbitkan pada 1953, disebutkan nama Samarinda diberikan karena pemerintahan dikendalikan orang-orang Bugis. Tidak seorang bangsawan Kutai pun di dalamnya. Makanya, orang Kutai menamakan ibu kota pemerintahan Bugis itu Samarinda. Artinya, pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang sesama rendahan (hlm 470). Untuk sementara, ini adalah sumber tertua mengenai penjelasan muasal penamaan Samarinda.
Pendapat lain disebutkan Oemar Dachlan pada 1978 yang mengungkapkan asal kata Samarinda dari istilah “sama rendah”. Permukaan tanah yang tetap rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik turun. Pada kemudian hari, Oemar Dachlan bergabung bersama Muhammad Noor Ars, Dachlan Syahrani, dan Amir Hamzah Idar menulis naskah buku Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda (MKSKS). Asal-muasal nama Samarinda dalam buku itu sebagai berikut:
“Dengan rumah rakit di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dan lainnya yang melambangkan ‘tidak ada perbedaan derajat, bangsawan ataukah rakyat biasa, semua sama derajatnya.’ Dengan lokasi di sekitar muara sungai dan kiri kanan sungai dataran rendah atau renda (bukan randah, pen). Diperkirakan, dari istilah inilah lokasi pemukiman tersebut dinamakan Samarenda atau lama kelamaan (dengan ejaan) menjadi Samarinda. Setelah diadakan permufakatan antara mereka, maka perkampungan itu diberi nama Samarenda yang berarti: tidak ada yang lebih tinggi keturunan bangsawannya (hlm 6).”
Mengenai asal usul nama Samarinda yang terakhir ini sebenarnya sudah diungkapkan Dahlan Sajrani dalam makalahnya pada 1987. Jadi, bukan pengertian baru yang dibuat saat MKSKS dituliskan pada 2003-2004.
Sebelumnya, memang, dalam De Kroniek Van Koetai, disebutkan bahwa telah ada nama-nama negeri di masa lalu yang sekarang menjadi bagian Samarinda. Dikabarkan, petinggi Hulu Dusun mengundang orang-orang dari Pulau Atas, Karang Asam, Orang Karang Mumus, Luah Bakung, Sambuyutan, dan Mangkupelas.
Yang harus diketahui, ketika Kerajaan Kutai berdiri, negeri-negeri tadi memakai hukum Kerajaan Kutai atau menjadi bagian dari Kutai. Negeri-negeri itu tak pernah disebut sebagai bagian Samarinda masa lampau. Toponimi Samarinda pada masa lalu jelas merujuk kepada wilayah khusus yang diberikan Kerajaan Kutai kepada pemukim Bugis.
Ketika Samarinda menjadi ibu kota Afdeeling Kutai pada 16 Agustus 1896, pemerintah Gubernemen Belanda menetapkan vierkante paal yang menjadi cikal-bakal Samarinda Kota. Batas-batasnya di sebelah utara, timur laut, dan barat adalah suatu daratan yang terletak sejajar dengan sungai Mahakam (berjarak 500 meter dari sungai tersebut). Di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Karangmumus, di barat dengan Sungai Karang Asam Besar, dan di selatan dengan sungai Mahakam.
“Semasih zaman Hindia Belanda, wilayah Samarinda seluas 1 paal persegi yakni formilnya. Langsung di bawah pemerintahan gubernemen (Hindia Belanda). Wilayah yang dikuasai/diperintah oleh Gubernemen ini, dalam Bahasa disebut rechtstreeks gouvernement bestuursgebied atau vierkante-paal gebied. Luasnya, menurut realitas ialah di sebelah hilir sampai di pinggir Karangmumus sebelah kiri. (Dengan demikian, wilayah sebelah kanan Sungai Karangmumus sudah termasuk kekuasaan kerajaan Kutai). Di sebelah hulu, sampai Telok Lerong. Di sebelah darat (utara) sampai kurang lebih 1 km dari pinggir Mahakam. Jadi, jalan raya yang membentang dari pinggir Karangmumus hilir sampai depan rumah wali kota di hulu sekarang ini (yang sampai sekitar 1948 masih semak-semak dan kebun penduduk), pada waktu itu termasuk daerah kekuasaan kerajaan Kutai,” demikian ditulis dalam Kotamadya Samarinda dan Pembangunan (1978, hlm 9-10).
Dampak penerapan vierkante-paal, jika ada orang yang terkena kasus hukum, ia dihukum menggunakan pengadilan Hindia Belanda. Jika pelanggaran terjadi di luar wilayah itu, dikenai hukuman sesuai hukum kerajaan Kutai. Bahwa sampai pembentukan vierkante-paal oleh Belanda pun, masih banyak wilayah yang kini menjadi bagian Kota Samarinda masih merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai, terpisah dari Samarinda.
Dalam perjalanannya, wilayah Samarinda berkembang dan susut berkali-kali. Wilayah desa maupun kecamatan yang dulunya masuk Samarinda seperti Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-sanga, kini masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Begitu juga wilayah pada masa lalu adalah daerah kekuasaan Kutai atau bukan Samarinda, belakangan menjadi bagian wilayah Samarinda.
Memposisikan La Mohang Daeng Mangkona
Mohd Noor Ars berdasarkan Lontarak Samarinda Seberang yang ditulis I Kirana Daeng Risompa, Kapitan Ranreng, cucu Puak Ado La Tojeng Daeng Rippeta, menyebutkan bahwa Samarinda dibentuk La Mohang Daeng Mangkonak pada 1708. Saat itu, orang-orang Bugis meninggalkan rumah rakit dan mendirikan rumah. Nama Samarenda pun diganti menjadi Samarinda tepat 20 April 1708. Data tersebut juga disampaikan Dahlan Sjahrani dalam makalahnya berjudul Beberapa Usaha Menemukan Hari Jadinya Samarinda, Makalah pada Seminar Hari Jadi Samarinda pada 4-5 September 1987 (hlm 10).
Menariknya, Puak Ado La Tojeng yang disebutkan Mohd Noor Ars itu disebut dalam Salasila Bugis bukan La Mohang Daeng Mangkona. Menurut naskah Tromp, yang membuat perjanjian dengan Sultan Kutai adalah Anakhoda Latoedji. Nakhoda atau Anakhoda adalah sebutan kapten kapal dagang Padewakang. Anakhoda La Tojeng ini pula yang terlibat dalam perpindahan ibu kota pemerintahan Kutai dari Jembayan ke Tenggarong.
“Perpindahan yang terakhir terjadi pada 1781 yaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Muslihuddin yang diawali dengan pendirian sebuah istana pada suatu tempat yang semula bernama ‘Tepian Pandan’. Tetapi kemudian oleh Pua Ado La Tojeng Daeng Ripetta orang Bugis, salah seorang pendukung dalam penobatan Sultan Muhammad Muslihuddin, Tepian Pandan diganti namanya dengan “Tangga Arung”. Tangga artinya rumah; Arung artinya raja. Sekarang menjadi Tenggarong,” tulis Asli Amin dalam (Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai hlm 46).
Kedekatan Sultan Muslihuddin dengan La Tojeng ini dijelaskan dalam Sejarah Daerah Kalimantan Timur. Ketika konflik perebutan takhta Kutai pada 1748, Aji Imbut (nama kecil Sultan Muslihuddin) yang baru berusia 11 tahun dan saudaranya Aji Kensan (Aji Intan) berusia 12 tahun dibawa Nakhoda La Tojeng dan Nakhoda Lambai ke Wajo. Di Wajo, kedua putra Sultan Muhammad Idris itu sempat bertemu datuknya yang bernama La Maddukelleng.
“Di Wajo, Aji intan dikawinkan dengan La Maliungeng Arung Paniki, putri dari La Parusi Petta Buranti. Sedangkan Aji Imbut dalam usia 25 tahun diangkat menjadi menteri kerajaan dan dikawinkan dengan Puak Abeng, saudara sepupu Nakhoda La Tojeng dan Puak Indek Lebbi,” tulis Sambas Wirakusumah dalam Sejarah Daerah Kalimantan Timur (1978, hlm 39).
Bagaimana dengan La Mohang Daeng Mangkona? Zainal Abidin dalam Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan tidak setuju La Mohang Daeng Mangkona Puak Ado pertama Samarinda datang bersama-sama La Maddukelleng Arung Singkang serta tiga putranya yaitu Petta To Sibengngareng, Petta To Siangka, dan Petta To Rawe. Oleh karena La Maddukelleng barulah datang di Pasir pada 1726. Sementara itu, orang-orang Wajo telah datang pada 1668 ketika La Maddukelleng belum lahir (hlm 208).
Zainal Abidin menolak pendapat bahwa La Mohang Daeng Mangkona datang bersama La Maddukeleng. Artinya, jika yang disampaikan Mohd Noor Ars bahwa La Mohang Daeng Mangkona telah berperan saat orang-orang Bugis naik dari rumah rakit ke daratan pada 1708, bisa disimpulkan La Mohang Daeng Mangkona datang lebih dulu di Samarinda dibanding kedatangan La Maddukelleng. Bisa jadi, La Mohang Daeng Mangkona menjadi tokoh yang lebih tua yang sejak lama menetap di Samarinda. Ia kemudian bergabung menjadi pendukung La Maddukelleng ketika mengetahui sang Pangeran Muda Wajo itu di Paser.
Jika membaca ulang buku Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda yang ditulis tokoh-tokoh sejarawan Kaltim, bisa ditangkap sudut pandang seperti ini. La Mohang Daeng Mangkona dianggap sebagai Pua Ado I yang memimpin sejak 1673 sampai 1746 atau selama 73 tahun. Artinya, ia telah menjadi Pua Ado dan tinggal di Samarinda bahkan sebelum La Maddukelleng lahir pada 1700. Ketika La Maddukelleng tiba di Pasir pada 1726, ia bergabung menjadi pengikut sang pangeran muda kemudian diperintahkan tetap menjadi Pua Ado di Samarinda. Dalam politik masa kini, banyak contoh nyata semisal politikus senior atau yang telah sepuh menjadi pendukung pemimpin yang lebih muda yang lahir belakangan.
Jika pun pada 1730 diperkirakan Anakhoda La Tojeng menjadi Pua Ado dan mengikat perjanjian dengan Sultan Kutai di Jembayan, harus diingat ia terlibat dalam penyelamatan dengan membawa putra mahkota Kutai ke Wajo. Anakhoda La Tojeng baru kembali bersama Aji Imbut dan diangkat sebagai Pua Ado semasa Sultan Muslihuddin. Sepanjang Samarinda ditinggal Anakhoda La Tojeng, bisa jadi jabatan itu dipegang kembali oleh La Mohang Daeng Mangkona sampai 1746.
_____________________________________________________INFOGRAFIK

Ada banyak cerita rakyat yang ditulis mengenai La Mohang Daeng Mangkona. Ada cerita rakyat berbahasa Kutai berjudul La Ma’dukelleng yang kemudian di-Indonesia-kan pada 1984 dan dimuat dalam Cerita-cerita Daerah Kalimantan Timur dan Cerita Rakyat dari Kalimantan Timur (1994). Daeng Mangkona dikisahkan sebagai pendiri Samarinda.
“Sementara, La Mohang Daeng Mangkona diterima di Kutai Lama. Kemudian pada 1672 mereka dianugerahi tanah di Samarinda Seberang sekarang untuk tempat tinggal mereka. Di tempat baru ini, La Mohang Daeng Mangkona diperkenankan mengatur anak buahnya sendiri menurut adat leluhurnya sendiri di tanah Wajo. Pada mulanya, mereka berdiam di rakit kemudian mereka membuat rumah di darat,” demikian tertulis dalam Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Timur (hlm 77).
Ada semangat yang bisa diambil dari kisah itu. La Mohang Daeng Mangkona, jika pun nanti secara historiografi dianggap pendiri atau bukan, tetap harus dipandang sebagai tokoh penting bagi sejarah tumbuhnya Samarinda. Namanya sejak lama telah menjadi bagian ingatan publik masyarakat Kutai dan Samarinda. (*)
Ditulis oleh: Chai Siswandi, tinggal di Kota Bangun, Kutai Kartanegara.
Baca juga tanggapan Muhammad Sarip terhadap naskah ini, Menjawab Klaim Daeng Mangkona Pendiri Kota dan Perlunya Merevisi Hari Jadi Samarinda.
Senarai Kepustakaan
-
Abidin, Andi Zainal, 1983. Persepsi Orang Bugis, Makasar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar, Penerbit Almuni: Bandung
-
Abidin, Andi Zainal, 1999. Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan. Cet I. Hasanuddin University Press: Ujungpandang.
-
Ahyat, Ita Syamtasiyah, 2013. Kesultanan Kutai 1825-1910 Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda, Serat Alam Media.
-
Amin, Mohammad Asli, dkk, 1975. Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai.
-
Dachlan, Oemar, dkk, 2004. Merajut Kembali Sejarah Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda.
-
Knappert, SC, Behschrijving Van De Onderafdeeling Kotei.
-
Moor, JH, 1837. Notices of The Indian Archipelago And Adjacent Countries. Singapore.
-
Nijhoff, S. Gravenhage Martinus, 1918. Encyclopedie van Naderlandsch Indie Edisi Kedua, Leiden.
-
Nijhoff, S-Gravenhage Martinus, 1939. Encyclopedie Van Nedelandsch-Indie. D.G Stibbe.
-
Pelras, Christian, 2005. Manusia Bugis. Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO. Jakarta.
-
Pemerintah Daerah TK II Kotamadya Samarinda, 1978. Kotamadya Samarinda dan Pembangunan.
-
Sjahrani, Dahlan, 1987. Beberapa Usaha Menemukan Hari Jadinya Samarinda. Makalah Seminar Hari Jadi Samarinda pada 4-5 September 1987.
-
Suwondo, Bambang (editor), 1984. Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Timur. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
-
Tromp, SW, 1888. Eenige Mededeeliengen Omtrent De Boeginesen Van Koetei.
-
Wirakusumah, Sambas, dkk, 1978. Sejarah Daerah Kalimantan Timur. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek penerbitan buku bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah: Jakarta.